BAB II
LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN
A. Pengertian Landasan Filosofis
Landasan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:260) istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fundasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal; suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal; atau suatu fundasi tempat berdirinya sesuatu hal. Berdasarkan sifat wujudnya terdapat dua jenis landasan, yaitu: (1) landasan yang bersifat material, dan (2) landasan yang bersifat konseptual. Contoh landasan yang bersifat material antara lain berupa landasan pacu pesawat terbang dan fundasi bangunan gedung. Adapun contoh landasan yang bersifat konseptual antara lain berupa dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD RI Tahun 1945; landasan pendidikan, dsb.
Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir (melakukan suatu studi) dan/atau dalam rangka bertindak (melakukan suatu praktek). Menurut Troy Wilson Organ, “asumsi dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu: aksioma, postulat, dan premis tersembunyi” (Redja Mudyahardjo, 1995). Aksioma adalah asumsi yan diterima tanpa persetujuan. Postulat adalah asumsi yang diajukan atas dasar persetujuan. Premis Tersembunyi asumsi yang tidak dinyatakan tesurat, yng diharapkan diphami dan diterima.
|
|
Dalam Burhanudin TR, dkk (2012:25) adanya landasan pendidikan dimaksudkan agar penyelenggaaan pendidikan didasrkan pada landasan hasil berfikir mendalam tentang kearifan dan kebijaksanaan dalam penyelenggaran pendidikan mulai dari perumusan tujuan, kurikulum, persepsi tentang pendidik dan peeserta didik, metode, media, dan evaluasi pembelajaran.
B. Landasan Filosofis Pendidikan Idealisme dan Realisme
1. Landasan Filosafis Pendidikan Idealisme
a. Konsep Filsafat Umum
Tatang Syarifudin, dkk, (2009:40) metafisika : Hakikat Realitas. Dialam semesta terdapat berbagai hal, seperti batu, air, tumbuhan, hewan, manusia, gunung, lautan, sepeda motor, dan sebagainya; selain itu, kita juga mengenal apa yang disebut jiwa, spirit, ide, dan sebagainya. Para filsuf idealisme mengklaim bahwa hakikat realitas bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Plato, bahwa dunia yang kita lihat, kita sentuh dan kita alami melalui indera bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan suatu dunia bayangan (a copy world); dunia yang sesungguhnya adalah dunia idea-idea (the world of “ideas”). Karena itu Plato disebut sebagai seorang idealist (S.E. Forst Jr, 1957). Bagi penganut idealisme realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental, yaitu pikiran/spirit/roh. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata, sesungguhnya diturunkan dari jiwa/pikiran/roh.
|
Berdasarkan uraian para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa, manusia adalah makhluk berfikir, mampu memilih/bebas, hidup dengan aturan moral yang jelas dan memiliki tujuan hidup.
Epistemology: Hakikat Pengetahuan. Proses mengetahui terjadi dalam pikiran, manusia memperoleh pengetahuan melalui berfikir. Disamping itu, manusia pula memperoleh pengetahuan melalui intuisi. Bagi penganut idealisme objective seperti Plato, ide-ide merupakan esensi yang keberadaannya bebas dari pendirian. Sedangkan bagi penganut idealisme subjective seperti George Barkeley, bahwa manusia hanya dapat mengetahui apa yang ia persepsi.
Aksiologi: Hakikat Nilai. Para filusuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai yang bersifat abadi. Menurut para penganut Idealisme Theisik nilai-nilai abadi berada pada Tuhan. Penganut Idealisme Pantheistik mengidentikan Tuhan dengan alam. Sebab itu dapat disimpulkan bahwa manusia diperintah oleh nilai-nilai moral imperative dan abadi yang bersumber dari Tuhan.
2. Implikasi terhadap Pendidikan
Tatang Syarifudin, dkk, (2009:42) tujuan pendidikan adalah untuk membantu perkembangan fikiran dan diri pribadi siswa. Sebab itu, sekolah hendaknya menekankan aktivitas-aktivitas intelektual, pertimbangan-pertimbangan moral, estetis, realitas diri, kebebasan, tanggungjawab, dan pengendalian diri demi mencapai perkembangan fikiran dan diri pribadi (Callahan and Clark, 1983). Dengan kata lain pendidikan bertujuan untuk membantu pengembangan karakter, bakat, dan kebajikan sosial.
|
Stuktur dan atmosfir kelas hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir, dan untuk menggunakan kriteria penilaian moral dalam situasi situasi konkret dalam konteks pembelajaran. Namun demikian, tidak cukup mengajar siswa bagaimana berfikir, adalah sangat penting bahwa apa yang siswa fikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan.
Para filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi dari para guru. Guru harus unggul (exellent) agar menjadi teladan bagi para siswanya dan secara moral maupun intelektual. Tidak ada satu unsur pun yang lebih penting didalam sitem sekolah selain seorang guru. Guru harus unggul dalam pengetahuan dan memahami kebutuhan-kebutuhan serta kemampuan-kemampuan para siswanya; dan harus mendemonstrasikan keunggulan moral dalam keyakinan dan tingkah lakunya. Guru juga harus melatih berfikir kreatif dalam mengembangkan kesempatan bagi fikiran siswa untuk menemukan, mengenalisis, memadukan, mensintesa, dan menciptakan aplikasi-aplikasi pengetahuan untuk hidup dan berbuat (Callahan and Clark, 1983).
3. Landasan Filosofis Pendidikan Realisme (Realisme Objektif)
a. Konsep Filsafat Umum
Metafisika: Hakikat Realitas. Menurut para filsuf realisme bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial, dan material yang hadir dengan sendirinya (entity). Dalam alam tersebut terdapat hokum-hukum alam yang menentukan keteraturan dan keberadaan setiap yang hadir dengan sendirinya dari alam itu sendiri (Callahan and Clark, 1983). Realitas hakikatnya bersifat objektif artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak tergantung atau tidak bersandar kepada fikiran/jiwa/spirit/roh. Manusia adalah bagian dari alam, dan ia muncul dialam sabagai puncak dari mata ranti evolusi yang terjadi dialam.
|
Aksiologi: Hakikat Nilai.karena manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hokum-hukum alam, demikian pula masyarakat.
b. Implikasi terhadap Pendidikan
Pendidikan pada dasarnya bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup didunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Dengan jalan memberikan pengetahuan yang esensial kepada para siswa, maka mereka akan dapat bertahan hidup dilingkungan alam dan sosial. Edward J. Power (1982) menyimpulkan pandangan para filsuf realisme bahwa tujuan pendidikan realism adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial.
Para filsuf Yunani percaya bahwa kurikulum yang baik diorganisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran. Metode pendidikan yang disarankan para filsuf realisme bersifat otoriter. Guru mewajibkan para sisiwa untuk menghapal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta; menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru.
Guru adalah pengelola kegiatan belajar mengejar didalam kelas; guru adalah penentu materi pelajaran; guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan meta pelajaran; dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untiuk dialami siswa.
|
1. Landasan Filosofis Pendidikan Pragmatisme
a. Konsep Filsafat Umum
Metafisika: Hakikat Realitas.Pragmatisme dikenal pula dengan sebutan Eksperimentalisme dan Instrumentalisme. Menurut aliran ini hakikat realitasn adalah segala sesuatu yang dialami manusia (pengalaman); bersifat plural (pluralistic); dan terus berubah. Mereka berargumentasi bahwa relitas adalah sebagaimana yang dialami melalui pengalaman setiap individu (Callahan and Clark, 1983).
Hakikat Manusia. Kepribadian/manusia tidak terpisah dari realitas pada umumnya, sebab manusia merupakan bagian daripadanya dan terus menerus bersamanya. Karena relitas ters berubah, manusia pun merupakan bagian dari perubahan tersebut.
Epistemologi: Hakikat Pengetahuan. Filsuf Pragmatisme menolak dualisme antara subjek (manusia) yang mempersepsi dengan objek yang dipersepsi. Manusia adalah kedua-duanya dalam dunia yang dipersepsinya dan dari dunia yang ia persepsi. Pengalaman tentang fenomena menentukan pengetahuan. Karena fenomena terus menerus berubah, maka pengetahuan dan kebenaran tentang fenomena itu pun mungkin berubah.
Pengetahuan dinyatakan benar apabila dapat dipraktekkan, memberikan hasil dan memuaskan. Pengetahuan bersifat relatif.
Aksiologi: Hakikat Nilai. Nilai-nilai diturunkan dari kondisi manusia. Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu dalam tindakan/perbuatan manusia itu sendiri.
|
Tujuan Pendidikan. Pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan-tujuan pendidikan meliputi:
1) Kesehatan yang baik
2) Keterampilan-keterampilan kejuruan (pekerjaan)
3) Minat-minat dan hobi-hobi untuk kehidupan yang menyenangkan
4) Persiapan untuk menjadi orang tua
5) Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial
Pendidikan juga harus meliputi pemahaman tentang pentingnya demokrasi. Menurut Pragmatisme, pendidikan hendaknya bertujuan menyediakan pengalaman untuk menemukan/memecahkan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan sosialnya (Edward and Clark, 1983).
Kurikulum Pendidikan. Dalam pandangan Pragmatisme, kurikulum sekolah seharusnya tidak terpisahkan dari keadaan-keadaan masyarakat. Karena itu masalah-masalah masyarakat demokratis harus menjadi bentuk dasar kurikulum; dan makna pemecahan ulang masalah-masalah lembaga demokratis juga harus dimuat dalam kurikulum. Karena itu kurikulum harus menjadi:
1) Berbasis pada masyarakat
2) Lahan praktek cita-cita demokratis
3) Perencanaan demokratis pada setiap tingkat pendidikan
4) Kelompok batasan tujuan-tujuan umum masyarakat
5) Bermakna kreatif untuk pengembangan keterampilan-keterampilan baru
6) Kurikulum berpusat pada siswa
Metode Pendidikan. Penganut Eksperimentalisme atau Pragmatisme mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah (Problem Solving Method) serta metode penyelidikan dan penemuan (Inquiry and Discovery Method).
|
a) Menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi.
b) Membimbing siswa untuk merumuskan batasan masalah secara spesifik.
c) Membimbing merencanakan tujuan-tujuan individual dan kelompok.
d) Membantu para siswa dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan masalah.
e) Bersama-sama kelas mengevaluai apa yang telah dipelajari.
C. Landasan Filosofis Pendidikan Scholastisisme
a. Konsep Filsafat Umum
filsafat St. Thomas Aquinas adalah filsafat resmi Gereja Katolik Roma. Filsafat ini disebut juga Scholastisisme. Dalam pemikiran sebagai scholastic, filsafat diberi peranan lenih rendah dari teologi.
Metafisika: Hakikat realitas. Menurut filsuf Scholastisisme bahwa alam semesta atau realitas adalah ciptaan Tuhan. Scholastisisme menganut prinsip hylemorphe. Prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu kecuali Allah dan Malaikat merupakan kesatuan dari materi dan bentuk. Prinsip ini memungkinkan kita memahami terjadinya perubahan.
Hakikat Manusia. Manusia adalah ciptan Tuhan. Manusia merupakan kesatuan baan jiwa.
Epistemologi: Hakikat Pengetahuan. Menurut para Scholastic bahwa kebenaran absolut dapat diperoleh manusia berdasarkan keimanan (faith). Tetapi manusia pun dapat memperoleh kebenaran tentang benda-benda melalui rasio atau akal.
|
b. Implikasi Terhadap Pendidikan
Tujuan Pendidikan. Pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan potensialitas manusia secara penuh menurut doktrin Scholastic. Karena manusia adalah rational being/animal rational, keseluruhan potensiya meliputi intelektual, fisikal, volisional (kemauan), dan vocasional.
Kurikulum Pendidikan. Isi pendidikan harus meliputi agama dan ilmu kemanusiaan (humanities).
Metode Pendidikan. Metode pendidikan yang diutamakan adalah metode mendisiplinkan pikiran (Disciplining the mind); latihan formal (formall drill); persiapan jiwa dan Catekhisme.
Peranan guru dan siswa. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Guru mempunyai wewenang untuk mengatur kelas.
Orientasi pendidikan Scholastisisme adalah Perennialisme (Callahan and Clark, 1983). Hal ini dapat dipahami karena pendidikan Scholastisisme menekankan pengetahuan pengetahuan dan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, absolue, menetap atau abadi, serta prinsipnya yang religius. Perennialisme memandang tugas pendidikan adalah untuk memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, universal, absolute dan abadi atau menetap tersebut yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang diakuinya sebagai kebudayaan yang ideal.
|
Dalam pembelajaran ini anda akan mengkaji landasan filosofis pendidikan. Konstruktivisme dan landasan filosofis pendidikan nasional (pancasila). Kajian dalam kedua landasan filosofis tersebut meliputi konsep filsafat umum masing-masing aliran yang bersangkutan, serta implikasi terhadap konsep pendidikannya. Dengan demikian setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini anda akan dapat memahami hakikat: realitas, manusia, pengetahuan,dan nilai menurut Konstruktivisme dan filsafat pendidikan nasional (pancasila); serta implikasinya terhadap pendidikan yang meliputi : tujuan pendidikan, isi/kurikulum pendidikan, metode pendidikan, serta peranan pendidik dan peserta didik.
1. Landasan Filosofis Pendidikan Konstruktivisme
a. Konsep Filsafat Umum
Tema utama filsafat Konstruktivisme yaitu berkenaan dengan hakikat pengetahuan. Filsafat konstruktivisme berimplikasi terhadap pendidikan. Von Glaserfeld (1988) mengemukakan bahwa pengertian konstruktivisme kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Tetapi gagasan pokok cikal bakal Konstruktivisme sesungguhnya sudah dimulai oleh Giambastista Vico, seorang epistemolog dari Italia.
Metafisika, Hakikat Realitas: Menurut Konstruktivisme, manusia tidak pernah dapat mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis. Yang dapat kita mengerti hanyalah struktur konstruksi kita akan sesuatu objek (Shapiro, 1994). Konstruktivisme memang tidak bertujuan mengerti realitas secara ontologis, tetapi lebih hendak melihat bagaimana kita menjadi tahu akan sesuatu.
Konstruktivisme menolak prinsip independensi dan objektivisme dari Realitas/Empirisme, yang menyatakan bahwa keberadaan realitas berdiri sendiri terlepas dari subjek pengamat, namun terbuka untuk dapat diketahui melalui pengalaman empiris.
|
Kriteria kebenaran. Bagi konstrutivist, kebenaran pengetahuan diletakkan pada viabilitas. Dengan kriteria ini, maka pengetahuan manusia ada taraf atau tingkatannya: ada pengetahuan yang cocok atau berlaku untuk banyak persoalan sampai dengan pengetahuan yang hanya cocok untuk beberapa persoalan saja.
Sifat pengetahuan. Sehubungan dengan hal diatas, maka pengetahuan memiliki sifat:
1. Subjektif, sebab pengetahuan lebih menunjuk pada pengalaman seseorang akan dunia daripada dunia itu sendiri
2. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain
3. Pengetahuan bukan barang mati yang sekaligus jadi, bukan tertentu dan deterministik, melainkan suatu proses yang terus berkembang; dan karena itu
4. Pengetahuan bersifat relatif. Sebab itu, nilai bagi konstructivist juga bersifat relatif.
b. Implikasi terhadap Pendidikan
Dalam konstruktivisme istilah pendidikan lebih diartikan sebagai mengajar. Bagi konstruktivist, mengajar bukan kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti partisipasi dengan pelajar dalam mengkonstruksi pengetahuan, membuat makna, mempertanyakan kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Jadi mengajar adalah suatu bentuk belajar sendiri (Bettencourt, 1989). Mengajar, dalam konteks ini adalah membantu seseorang berpikir secara benar dengan membiarkanya berpikir sendiri (Von Glasersfeld, 1989). Dalam kegiatan mengajar penyedia prasarana dan situasi yang memungkinkan dialog secara kritis perlu dikembangkan.selain itu perlu diperhatikan pula bahwa mengajar juga adalah suatu seni yang menuntut bukan hanya penguasaan teknik, melainkan juga intuisi (Paul Suparno, 1997).
|
Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusanya termasuk dalam “Pembukaan” UUD Negara RI tahun 1945. Karena Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional.
a. Filsafat Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pendidikan
Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. Untuk mendapat pengertian yang mendalam dan mendasar, kita harus mengetahui sila-sila yang membentuk pancasila itu. Berdasarkan pemikiran filsafat, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD 1945 Alinia IV adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah satu nilai. Nilai-nilai yang merupakan perasaan dan Pancasila tersebut adalah:
1. Nilai Ketuhanan
2. Nilai Kemanusiaan
3. Nilai Persatuan
4.
|
5. Nilai Keadilan
Nilai itu selanjutnya menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia. Secara etimologi, nilai berasal dari kata value (Inggris) yang berasal dari kata valere (Latin) yang berarti: kuat, baik, berharga. Dengan demikian secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang berguna. Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indera, yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai bersifat normatif, suatu keharusan (dassolen) yang menuntut diwujudkannya dalam tingkah laku. Nilai juga menjadi pendorong/motivator hidup manusia.
Dalam filsafat Pancasila terdapat tiga tingkatan nilai yaitu, nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis.
1. Nilai Dasar
Nilai dasar adalah nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang besar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar itu sendiri dalam Pancasila adalah nilai-nilai dari sila-sila Pancasila.
Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap.
2. Nilai Instrumental
Nilai instrumental yaitu nilai yang berfungsi sebagai pelaksana umum dari nilai dasar. Umumnya terbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
3. Nilai Praktis
Nilai praktis yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia.
|
Sehubungan dengan hal di atas, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Kita perlu mengkaji nilai-nilai pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan.
Implikasi Filsafat Pancasila Bagi Pendidikan Nasional
1. Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Sebagai usaha sadar dan terencana, pendidikan tentunya harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas, sehingga dengan demikian isi pendidikan maupun cara-cara pembelajarannya dipilih, diturunkan, dan dilaksanakan dengan mengacu kepada dasar dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Selain itu,m pendidikan bukanlah proses pembentukan peserta didik untuk menjadi orang tertentu sesuai kehendak sepihak dari pendidik. Karena peserta didik pada hakikatnnya adalah pribadi yang memiliki potensi dan memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri, maka upaya pendidikan harus dipandang sebagai upaya bantuan dan memfasilitasi peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Upaya pendidikan adalah pemberdayaan peserta didik. Hal ini hendaknya tidak dipandang sebagai upaya dan tujuan yang bersifat individualistik semata, sebab sebagai mana telah dikemukakan bahwa kehidupan manusia itu multidimensi dan merupakan kesatuan yang intregral.
|
2. Tujuan Pendidikan
Pandangan Pancasila tentang hakikat realitas, manusia, pengetahuan, dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan seyogyanya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
3. Kurikulum Pendidikan
Kurikulum disusun dalam jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa, b) peningkatan akhlak mulia, c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, d) keragaman potensi daerah dan lingkungan, e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, f) tuntutan dunia kerja, g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, h) agama, i) dinamika perkembangan global, dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
4. Metode Pendidikan
Berbagai metode pendidikan yang ada merupakan alternatif untuk diaplikasikan. Sebab, tidak ada satu metode mengajar pun yang terbaik dibanding dengan metode lainnya dalam segala konteks praktek pendidikan. Pemilihan dan aplikasi metode pendidikan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, hakikat manusia atau peserta didik, karakteristik isi/materi pendidikan, dan fasilitas alat bantu pendidikan yang tersedia.
5. Peranan Pendidik dan Peserta Didik
Pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didiknya, pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya, dan sepanjang tidak berbahaya pendidik harus memberi kebebasan atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri.
6.
|
Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Konsep konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai, pengetahuan, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi dan dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Sedangkan fungsi kreasi dilandasi asumsi bahwa realitas tidaklah bersifat terberi dan telah selesai sebagaimana diajarkan oleh sains modern.
a. Konsep Filsafat Umum
Metafisika: Hakikat Realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan (makhluk) Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada, Ia adalah sebab pertama dari segala sebab, tetapi Ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang laiunnya: dan Ia juga adalah tujuan akhir segala yang ada.
Hakikat manusia, Manusia adalah makhluk Tuhan YME. Manusia adalah kesatuan badani-rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran dan penyadaran diri, mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta memiliki tujan hidup. Manusia dibekali potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan untuk berbuat baik, namun disamping itu karena hawa nafsunya manusaia pun memiliki potensi untuk : mampu berfikir (cipta), berperasaan (rasa), berkemauan (karsa), dan bekarya. Adapun dalam eksistensinya manusia berdimensi individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religius. Adapun semua itu menunjukan dimensi interaksi atau komunikasi (vertikal maupun horizontal, historisitas, dan dinamika.
Pancasila mengajarkan bahwa eksistansi manusia bersifat mono-pluralis tetapi bersifat integral, artinya bahwa manusia yang serba dimensi itu hakikatnya adalah satu kesatuan utuh. Pancasila menganut asas ketuhanan yang maha Esa: manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan YME, mendapat panggilan tugas darinya, dan harus mempertanggungjawabkan semua amal pelaksanaan tugas terhadap Tuhan YME (aspek religius ; asas mono dualisme : manusia adalah kesatuan badani-ruhani, ia adalah pribadi tetapi sekaligus insan sosial : asas mono pluralisme meyakini keragaman manusia, baik tunggal ika ; asas nasionalisme : dalam eksistensinya manusia terkait oleh ruang dan waktu, maka ia mempunyai relasi dengan daerah, jaman, dan sejarahnya yang diungkapkan dengan sikapnya mencintai tanah air, nusa, dan bangsa; asas internasionalisme: manusia Indonesia tidak meniadakan eksistensi manusia lain baik sebagai pribadi, kelompok, atau bangsa lain; asas demokrasi: dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama, kesamaan hak dan kewajiban menjadi dasar hubungan antar warga negara, dan hubungan antar warga negara dan negara dan sebaliknya; asas keadilan sosial: dalam merealisasikan diri manusia harus senantiasa menjunjung tinggi tujuan kepentingan bersama dalam membagi hasil pembudayaannya (BP-7 Pusat, 1995).
|
b. Implikasi terhadap Pendidikan
Pendidikan.pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama,pengendalian diri,kepribadian,kecerdasan,akhlak mulia,serta ketereampilan yang di perlukan dirinya,masyarakat,bangsa dan negara ( pasal 1 UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional)
Tujuan Pendidikan.pandangan pancasila tentang hakikat realitas,manusia,pengetahuan dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan seyogyanya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
|
Metode pendidikan. Berbagai metode pendidikan yang ada merupakan alternatif untuk diaplikasikan. Sebab, tidak ada satu metode mengajar pun yang terbaik dibanding metode lainnya dalam segala konteks pendidikan.
Peranan pendidik dan peserta didik. Ada berbagai peranan pendidik dan peserta didik yang harus dilaksanakannya, namun pada dasarnya berbagai peranan tersebut tersurat dan tersirat dalam semboyan: “ing ngarso sung tulodho” artinya pendidik harus memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya; “ing madya mangun karsa” artinya pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya; “tutwuri handayani” artinya bahwa sepanjang tidak berbahaya pendidik harus memberi kebebasan atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri.
Orientasi pendidikan. Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Fungsi konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai, pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan, dsb. Yang dijunjung tinggi dan dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Adapun fungsi kreasi dilandasi asumsi bahwa realitas bersifat terberi (given) dan telah selesai sebagaimana diajarkan oleh sains modern.


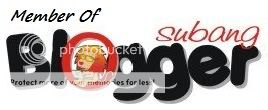

















0 komentar:
Post a Comment